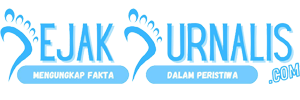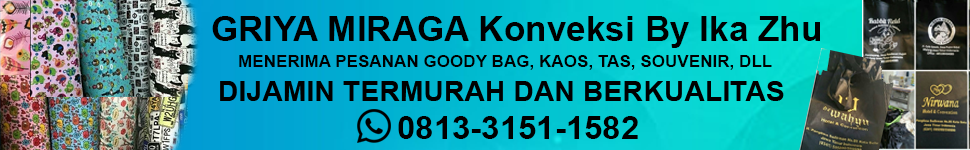Oleh : Wiwied Tuhu P. SH., MH
Sebelumnya ijinkanlah penulis mencuplik sepenggal Hadist Riwayat Tirmidzi, yang kurang lebihnya berbunyi seperti ini :“Barangsiapa yang dijadikan hakim diantara manusia, maka sungguh ia telah disembelih tanpa menggunakan pisau”
Peringatan tersebut berlaku secara umum dan menyeluruh, tidak terpisah-pisah. Ketika seorang Hakim sepanjang hayatnya menjalankan amanah tersebut dengan benar dan bersungguh-sungguh maka selamatlah dia, tetapi sekalipun sepanjang menjalankan tugas dia amanah dan bersungguh-sungguh dan diakhir masa tugasnya ia terbeli maka runtuhlah semuanya. Itu pulalah antara janji dan ancaman Allah berimbang kepada seorang Hakim, sebab manakala putusan Hakim bisa dibeli, maka runtuhlah keadilan. Dalam hal ini untuk menilai suatu perkara, seorang hakim tidak semata-mata merujuk pada aturan yang telah ada, tetapi juga dituntut untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU 48 Tahun 2009). Demikianpun seorang Hakim tidak diperkenankan menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 10 ayat (1) UU 48 Tahun 2009)
Di dalam hukum formil peradilan di Indonesia, mendudukkan Hakim sebagai penentu keadilan yang secara teori tidak dapat diintervensi oleh apapun dan siapapun, hal ini mewujudkan sosok Hakim sebagai wakil Tuhan dengan kekuasaan mutlak, dan bahkan Hakim dimungkinkan untuk hanya bersandar pada keyakinannya memberikan penilaian atas sesuatu hal, selanjutnya apapun putusan yang dibuat oleh Hakim harus dianggap benar (azas Res judicata pro veritate habetur), keadaan tersebut telah secara tidak langsung menempatkan masyarakat hanya berada diluar pagar kekuasaan penentuan keadilan, pada waktu Hakim memberikan penilaian atas perkara yang diperiksanya, padahal dasar eksistensinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan.
Pada kenyataannya seorang Hakim adalah pribadi yang dibentuk oleh suatu lembaga formal untuk berkarir sebagai Hakim dan ditempatkan disuatu wilayah tertentu di Indonesia, tanpa harus memperhatikan keselarasan antara latar belakang adat, adab, sosial budaya, strata, kelas dan lain sebagainya dari Hakim yang bersangkutan dengan tempatnya bertugas menjadi Hakim, yang hal ini menjadi salah satu penyebab potensi gangguan keserasian antara keadilan menurut Hakim dengan yang menurut Masyarakat, potensi permasalahan lainnya adalah dalam banyak perkara telah terjadi penyalah gunaan kewenangan dari Hakim yang dicatat oleh masyarakat, yang hal ini menunjukkan bahwa sistem untuk menjaga Hakim selalu ada di dalam khitohnya sebagai wakil Tuhan untuk mengejawantahkan keadilan masyarakat di Indonesia masih belum sempurna.
Tidak sempurnanya eksistensi Hakim sebagai wakil Tuhan bisa disimak dari hasil catatan detik.com mengenai 21 celah koruptif dalam proses peradilan, yang mana mulai hulu sampai hilir proses peradilan adalah masih terdapat celah-celah yang membuka peluang melakukan korupsi, dan keputusan Hakim sebagai pamungkas proses hukum sangat berpeluang besar membuka pintu korupsi, sehingga banyak Hakim telah dihukum penjara karena keputusannya merupakan pesanan, seperti misalnya terjadi pada Hakim Muhtadi Asnun, Amir Fauzi, Dermawan Ginting hingga Akil Mochtar, dll, juga dapat disimak dari berita mengenai ditangkapnya oleh KPK seorang Hakim Tripeni Indarto yang merupakan terbaik kedua calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015, dan perkara ini juga bukan yang pertama kali sebab Taufiequrrohman Syahuri salah satu komisioner Komisi Yudisial periode tahun 2010-2015 menyampaikan, bahwa sebelumnya sudah ditangkap beberapa hakim yang terjerat perkara seperti Heru Kusbandono (Hakim Tipikor Pontianak), Imas Dianasari (Hakim PHI Bandung), Syarifuddin Umar (Hakim PN Jakarta Pusat), Herman Alossitandi (Hakim PN Jakarta Selatan) yang hal itu dinyatakan karena kebiasaan lama oknum Hakim menerima suap saat menangani suatu perkara, juga ada Hakim lainnya yang ditangkap seperti Kartini Marpaung (Hakim Tipikor Semarang), Setyabudi Tejocahyono (Hakim PN Bandung).
Dari realitas seperti tergambarkan diatas, Proses peradilan di Indonesia ternyata masih sering menunjukkan kaburnya orientasi antara menegakkan hukum atau menegakkan keadilan, padahal sebenarnya jika tujuan peradilan adalah untuk mencari keadilan, maka penegakan hukum akan tercakup dengan sendirinya, sebab di dalam proses mencari keadilan maka pertama-tama yang dilakukan adalah dengan menggunakan alat hukum formil yang berlaku, dan barulah jika ketentuan di dalam hukum formil tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, ketentuan hukum formil sebagaimana dimaksud akan diabaikan, dan semestinya dapat dikenali perihal mana yang lebih fundamental dibutuhkan oleh masyarakat antara tegaknya hukum atau terpenuhinya keadilan.
Ketentuan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, selanjutnya ketentuan tersebut diperbaiki oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan kemudian juga diperbaiki di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”, ternyata ketentuan tersebut masih bersifat utopis sebab dari semenjak berlakunya UU No.14 Tahun 1970 sampai dengan sekarang, yakni berlakunya UU No.48 Tahun 2009, kesemua undang-undang tersebut diberlakukan tanpa ada cara yang efektif untuk memastikan dan menegakkan ketentuan “wajib” di dalam pasal undang-undang tersebut, yang mana setiap Hakim dikarenakan kewajibannya terjamin pasti akan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
Moh. Mahfud M.D menyatakan “kita sering mendengar Hakim membuat putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, tetetapi Hakim berlindung dibawah (atas nama) kebebasan untuk memutus perkara sesuai keyakinannya”, dari pendapat tersebut dapat penulis rasakan prasangka mengenai keputusan Hakim yang menciderai rasa keadilan masyarakat adalah disebabkan “kebebasan dalam keyakinan” Hakim untuk memutus perkara dapat dimanipulasi sedemikian rupa, karena nyatanya tidak ada mekanisme konkrit sebagai kanal untuk memastikan bahwa nilai dan rasa keadilan masyarakat tersalurkan kedalam ruang uji keadilan dalam lembaga peradilan, maka artinya klausula “wajib” pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman hanya digantungkan pada pribadi masing-masing Hakim yang sedang menilai keadilan, dan tentu mengingat arti penting keadilan sebagai nilai dasar yang hendak dipastikan terwujud melalui pranata hukum, adalah tidak tepat jika perwujudannya ternyata tidak dapat dipastikan melalui suatu mekanisme teknis tertentu, karena hanya akan diperoleh secara untung-untungan, melalui sosok hakim yang taat azas (meski tanpa sangsi), sedangkan disisi lain sebagaimana telah penulis sampaikan, keadilan itu sendiri bersifat dinamis bahkan relative dan sangat rupa-rupa ragamnya sehingga tidak mudah dipahami oleh seorang pribadi manusia yang baik sekalipun.
Masyarakat yang hanya dijadikan obyek oleh lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga penerap sangsi (dalam hal ini diartikan jauh atau bahkan tidak terlibat langsung dalam pembuatan hukum dan penerapan sangsi), telah sering menyebabkan keadilan yang dibuat oleh lembaga Peradilan tidak dirasakan sebagai keadilan oleh masyarakat, dan memang pada kenyataannya masyarakat tidak memiliki kanal atau saluran untuk dapat memasukkan nilai keadilan yang didambakannya akan secara konkrit mewarnai keputusan Hakim dalam menentukan keadilan, padahal nilai-nilai dasarnya sebenarnya keadilan itu adalah dimaksudkan untuk masyarakat, dan mana di dalam hukum pidana positif di Indonesia, Hakim mempunyai kewenangan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (strafsoort) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternative di dalam pengancaman pidana di dalam undang-undang.
Bukan hanya tidak ada kanal aspirasi rasa keadilan masyarakat untuk turut mempengaruhi putusan keadilan yang menyebabkan terdapat kesenjangan antara kebutuhan rasa keadilan masyarakat dengan putusan pengadilan yang menentukan keadilan, kesenjangan tersebut juga diperparah dengan keadaan bahwa dalam banyak hal ternyata putusan pengadilan seringkali tidak didukung dengan data ilmiah berdasarkan penelitian yang memadai (bisa diketahui dari banyaknya putusan peradilan pidana yang dalam pertimbangannya hanya dipengaruhi oleh aspek hukum saja tanpa kajian ilmiah berdasarkan disiplin ilmu yang kompleks), yang kiranya jika data hasil penelitian atas segala aspek yang berkaitan dengan suatu perkara disajikan kepada masyarakat sebagai pamilik hak atas rasa keadilan yang harus dipenuhi, maka secara obyektif akan menentramkan batin masyarakat itu sendiri untuk menerima keadilan yang disajikan oleh lembaga peradilan, sebab jikalau suatu keputusan lembaga peradilan tersebut dianggap tidak tepat oleh masyarakat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial sebab keadilan dalam hal ini adalah bergantung dari sudut pandang mana melihatnya.
Sebagai contoh ilustrasi adanya perbedaan persepsi yang dapat menciptakan penafsiran rasa keadilan beragam di dalam masyarakat yang beragam pula adalah antara lain termasuk tetapi tidak terbatas:
Perbedaan keyakinan kepercayaan yang memiliki unsur religiusitas atau keagamaan, yang dengan sumber berbeda dapat mempengaruhi masyarakat untuk menilai benar atau salah. Dalam tataran praktis dapat diambil contoh misalnya seorang suami dalam Agama Islam ada yang meyakini sebagai memiliki hak untuk memukul istrinya ataupun anaknya dalam suatu keadaan tertentu, yang hal ini belum tentu diterima sebagai kebenaran oleh masyarakat yang menganut keyakinan berbeda.
Perbedaan pemaknaan rasa bahasa, seperti misalnya kata “awas” yang dapat ditafsirkan sebagai ancaman atau peringatan atau minta perhatian, atau juga kata “jancok” yang dapat ditafsirkan berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda pula, misalkan ditafsirkan sebagai memarahi atau melecehkan atau mengancam atau bergurau atau sekedar panggilan ataupun kata penutup kalimat yang tidak memiliki arti.
Perbedaan kebiasaan atau kelaziman di dalam masyarakat, misalkan pernikahan dengan anak dibawah umur, pencurian dalam keluarga, mengkonsumsi ganja, membawa benda tajam, mengadu hewan, membawa perempuan, penganiayaan dan lain sebagainya.
Sampai dengan saat ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas menyampaikan aspirasi melalui media massa yang itupun tidak memiliki hubungan langsung dengan lembaga peradilan untuk mempengaruhi atau paling dalam hanya sekedar melakukan eksaminasi publik, yang eksaminasi publik ini dimaksudkan untuk melihat apakah suatu putusan (perkara yang sudah diputuskan) dari lembaga peradilan telah sesuai dengan penerapan ilmu pengetahuan hukum serta rasa keadilan masyarakat di dalam proses pengambilan keputusannya, pada suatu keadaan seperti ini kemudian menjadi rawan tumbuh kembangnya penyalahgunaan kekuasaan hukum dengan proses peradilan berproses di balik pintu tertutup, dan pelaksanaan hukum hanya tunduk pada pemegang kekuasaan yang memiliki proteksi secara ekonomi dan atau politik sebab hukum hanya berfungsi sebagai bagian dari administrasi yang melegitimasi kehendak penguasa, yang bilamana keadaan seperti itu yang terjadi sudah barang tentu gagal untuk terwujudnya keadilan dan daulat rakyat sebab berarti tidak ada keterlibatan peran serta rakyat dengan tercipta suatu keadaan dari rakyat-oleh rakyat dan untuk rakyat.
Sedangkan keadilan itu sendiri sudah diamanatkan di dalam Pancasila setidaknya di dalam sila ke-lima yang menyebutkan bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dengan sila keadilan sosial ini, manusia Indonesia harus sadar hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan secara proporsional, yaitu adil sesuai hakikat kodrat manusia sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Keadilan proporsional manusia dapat menghindari sifat tidak terpuji, seperti: rakus, korup, ingin menang sendiri, sewenang-wenang/dhalim dan bengis, juga dituangkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang Dasar NRI 1945 setidaknya pada bagian pembukaan alinea ke-dua dan alinea ke-empat. Keadilan juga dimaksudkan untuk memberikan persamaan hak untuk mendapatkan kesempatan perlindungan yang sama antara pribadi-pribadi penduduk Indonesia.
Dari paparan di atas dapat Penulis sampaikan bahwasannya perbedaan latar belakang adat, adab, sosial budaya, strata, kelas dan lain sebagainya yang membentuk pribadi Hakim dengan yang membentuk masyarakat telah rawan memunculkan disharmoni atau bahkan kesenjangan antara keadilan yang dibuat oleh penentu keadilan dalam hal ini Hakim dengan keadilan yang didambakan oleh masyarakat, sebab sebagaimana pendapat Satjipto Raharjo dalam menilai budaya hukum penegak hukum, menyatakan bahwa Hakim sendiri sebagai penegak hukum juga dipengaruhi oleh ciri sosial dari pribadi Hakim, latar belakang perorangan dari seorang Hakim (mobilitas geografi, kelas sosial, dan latar belakang keluarganya), pola pendidikan dan kondisi konkrit yang dihadapi oleh Hakim.
kemudian ditambah dengan kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Hakim menimbulkan potensi untuk kesewenang-wenangan Hakim menentukan keadilan yang akan disuapkan kepada masyarakat akan sangat tinggi, sebab masyarakat tidak dapat turut mengontrol dan menentukan keadilan untuk masyarakat itu sendiri secara konkrit, atau bahkan kalaupun dilihat dari sudut pandang positif Hakim adalah orang-orang suci dan terpilih melalui mekanisme yang jujur, ketat dan adil untuk kemudian dipersyaratkan bersumpah atas nama Tuhannya masing-masing akan menjalankan kewenangannya dengan itikat baik sehingga tidak akan mungkin untuk menyalahgunakan kewenangannya, maka tetap saja terdapat titik rawan keadaan seorang Hakim akan dapat menafsirkan nilai keadilan untuk suatu masyarakat tertentu berbeda dengan keadilan yang didamba oleh Masyarakat yang bersangkutan, sebab keadilan bukan hanya dipelajari dari teks-teks buku dan atau perihal perhitungan bersifat numerik yang baku, melainkan adalah berkenaan dengan rasa batin yang ditunjang oleh hati nurani yang telah diasah oleh adat, adab, sosial budaya, strata, kelas, pengalaman-pengalaman dalam hidup dan lain sebagainya semenjak setiap pribadi/individu dilahirkan sampai dengan saat sekarang memenuhi perikehidupannya dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, artinya dalam hal ini suatu nilai rasa keadilan menurut satu sudut pandang, tidak dapat dijejalkan begitu saja kepada suatu masyarakat untuk dapat diterima sebagai keadilan yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat yang telah nyata ragamnya.
Penulis merupakan pegiat Sosio Humaniora yang juga selaku Managing Partner dalam Kantor Hukum Asmojodipati.
Disclaimer : (Adapun artikel ini dimuat berdasarkan sepenuhnya bersumber dari penulis, yang mana konten serta muatannya tidaklah bermaksud merendahkan pihak manapun, melainkan sebatas buah pemikiran penulis yang menjadi aspirasi pribadi yang melekat dari dan oleh penulis).